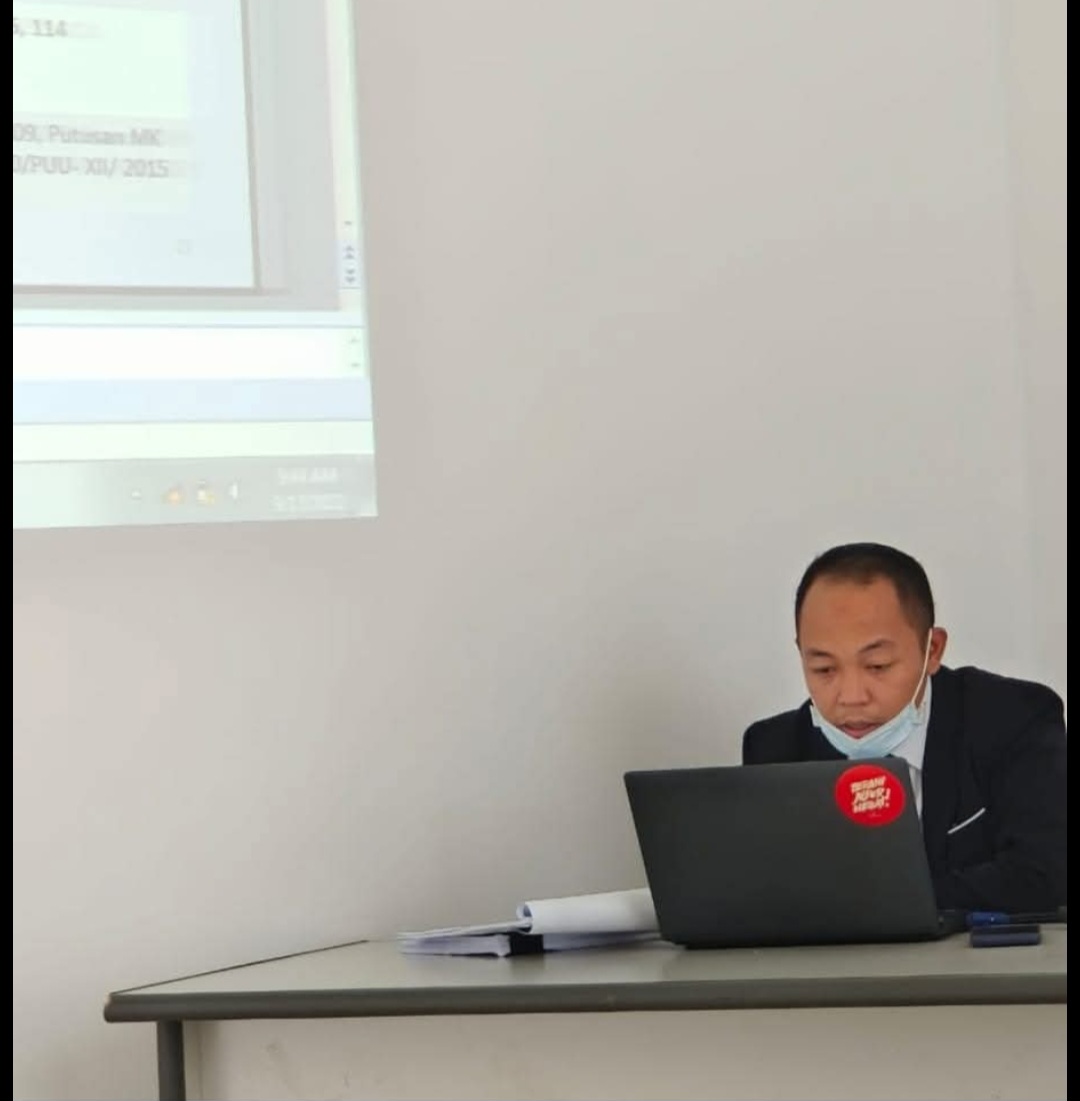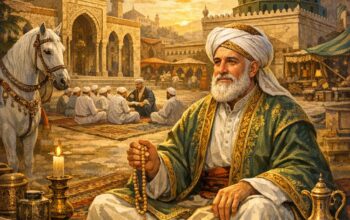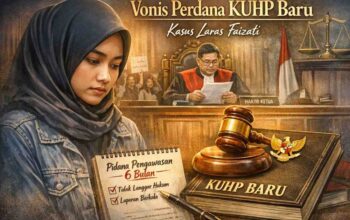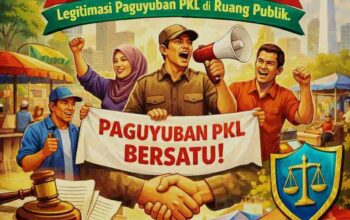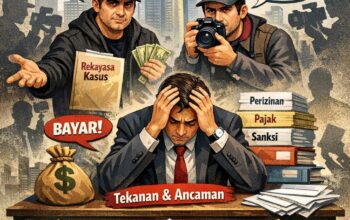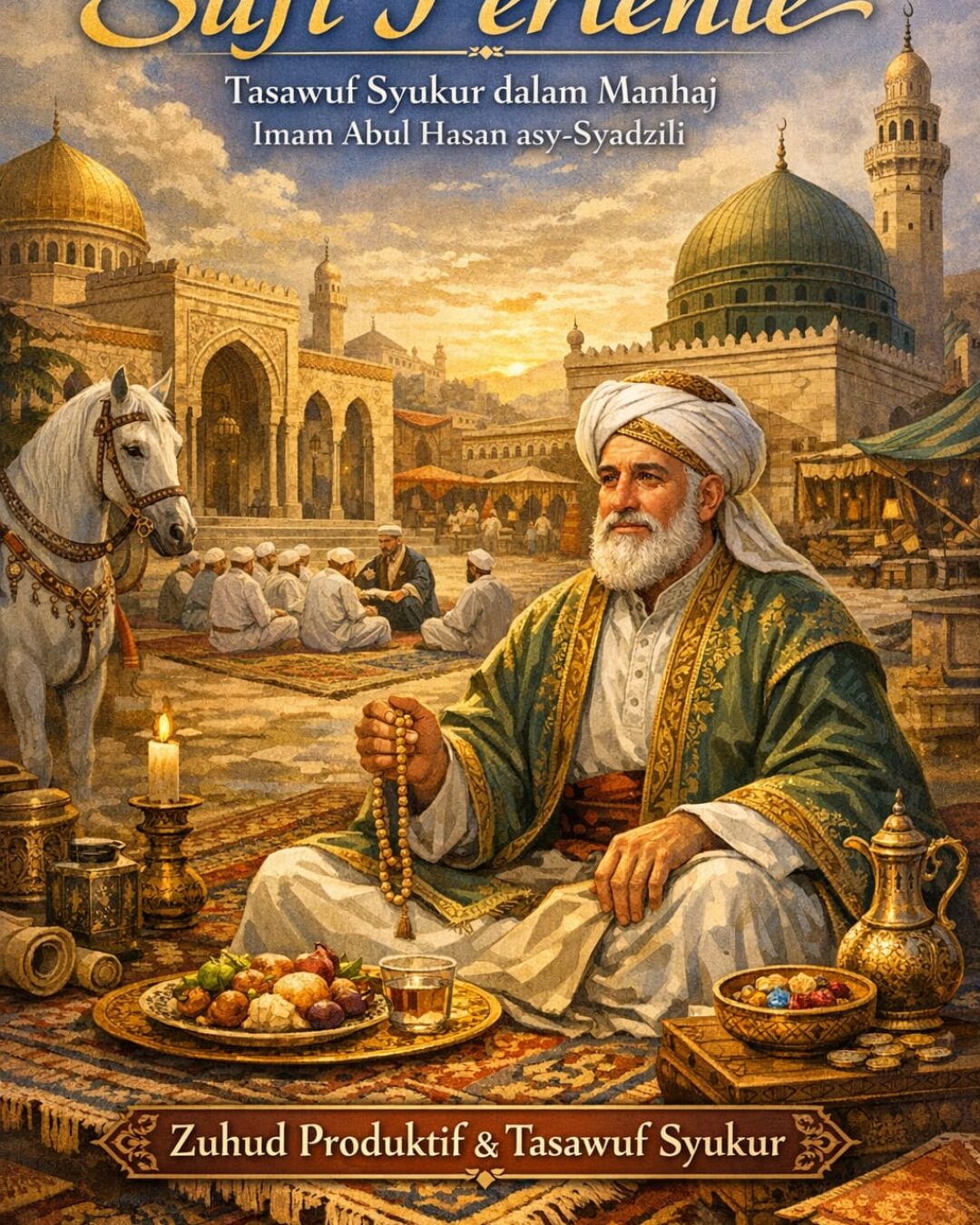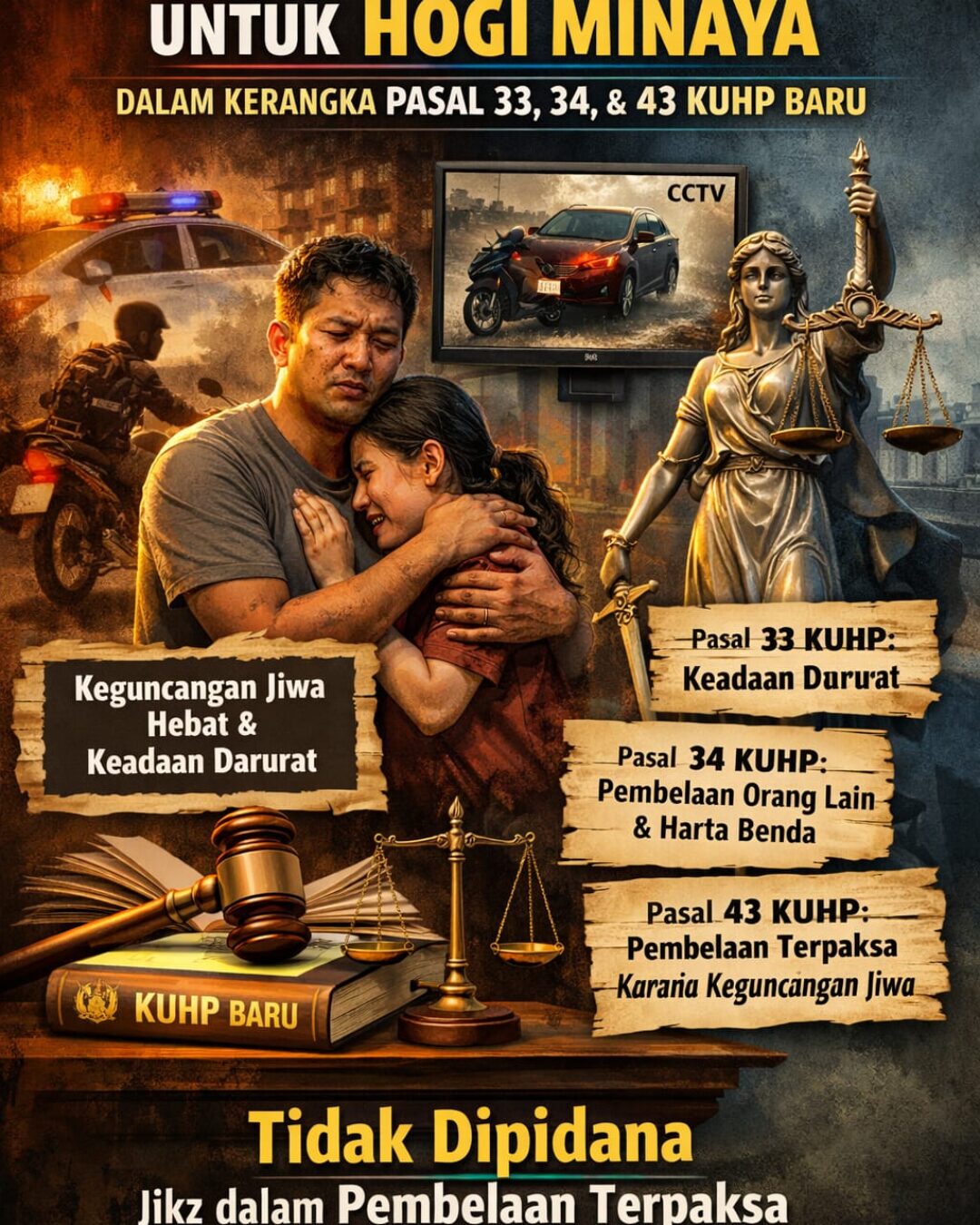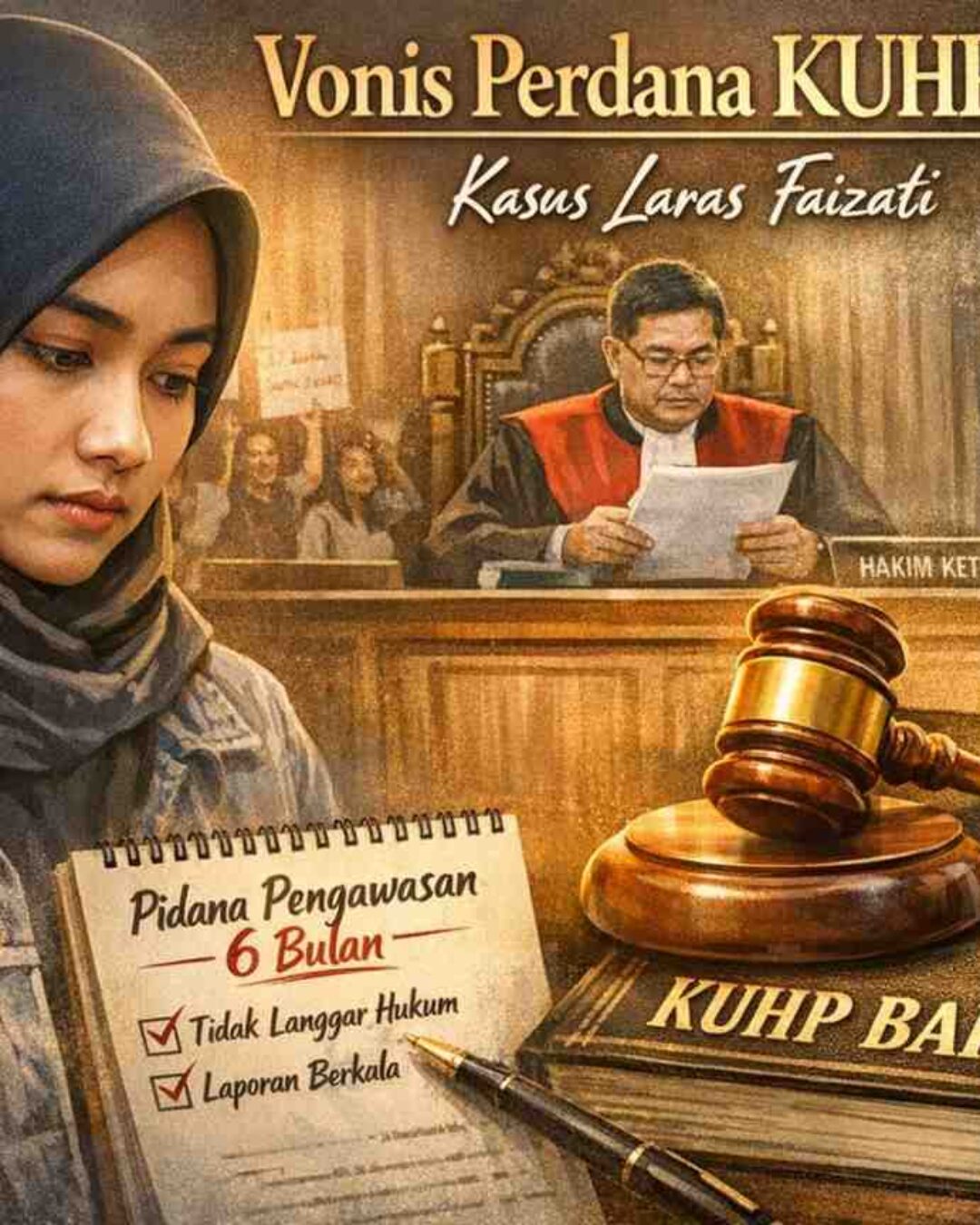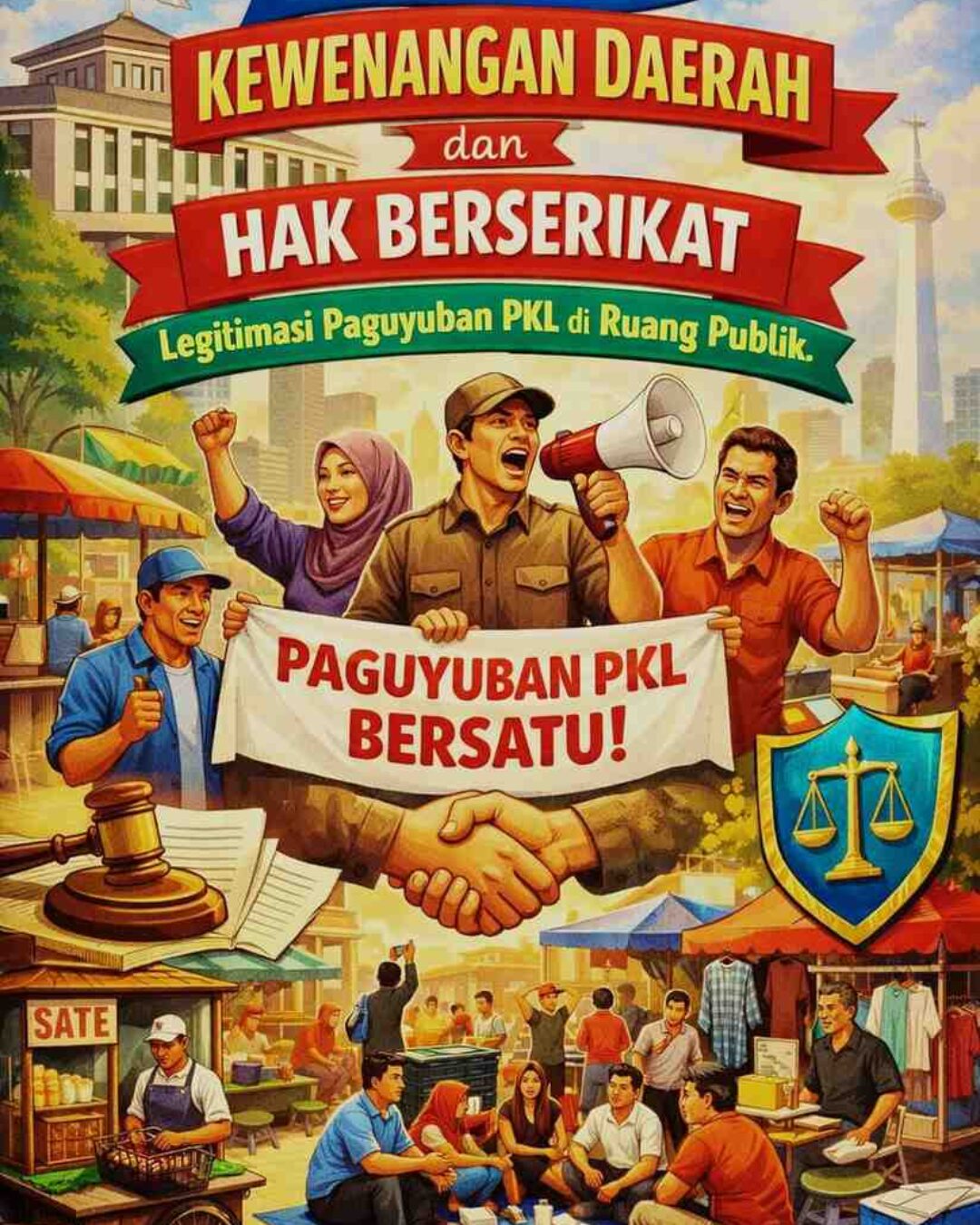Dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan kewajiban fundamental yang tidak bergantung pada keberadaan atau ketidakjelasan penghasilan yang bersangkutan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Norma ini diperkuat oleh Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman kepada istri, sekalipun istri mampu memberikan nafkah bagi dirinya sendiri.
Permasalahan timbul ketika dalam persidangan, penghasilan suami tidak dapat dibuktikan secara pasti karena tidak adanya bukti formal (slip gaji, surat keterangan kerja, laporan usaha, atau dokumen pajak). Dalam situasi demikian, hakim tetap berkewajiban menetapkan nominal nafkah yang pasti (determinatif) agar putusan memiliki kepastian hukum (rechtzekerheid) serta dapat dilaksanakan (executabel).
Untuk mengatasi kendala ketidakjelasan penghasilan, pendekatan doktrinal dan yurisprudensial memperlihatkan bahwa hakim menggunakan standar objektif berupa Upah Minimum Regional (UMR/UMK/UMP). Pertimbangan ini didasarkan pada tiga argumentasi utama:
1. Asas Kepatutan dan Keadilan (billijkheid en rechtvaardigheid)
Hakim tidak dapat menggantungkan penetapan nafkah pada dugaan semata. Oleh karena itu, standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah setiap tahun dianggap mencerminkan penghasilan rata-rata terendah seorang pekerja di wilayah tertentu. Dengan demikian, patokan UMK/UMP dianggap adil, wajar, dan obyektif untuk menggambarkan potensi penghasilan minimal seorang suami.
2. Asas Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Dalam perspektif konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nafkah adalah instrumen hukum untuk menjamin hak-hak tersebut. Oleh karenanya, penetapan nafkah tidak boleh nihil hanya karena penghasilan suami tidak diketahui, sebab hal itu akan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi, yaitu istri dan anak.
3. Preseden Yurisprudensi
Dalam sejumlah putusan pengadilan agama, majelis hakim menggunakan UMK daerah sebagai dasar estimasi penghasilan suami. Selanjutnya hakim menetapkan nafkah dengan proporsi tertentu, umumnya berkisar antara ⅓ hingga ½ dari nilai UMK, disesuaikan dengan jumlah tanggungan dan kondisi faktual masing-masing pihak.
Dengan demikian, ketika penghasilan suami tidak diketahui secara pasti, hakim harus menetapkan nafkah berdasarkan ukuran objektif berupa UMK/UMP daerah, dikurangi atau disesuaikan dengan proporsi tertentu yang memperhatikan asas kepatutan, keadilan, serta kebutuhan nyata istri dan anak.
Konstruksi hukum ini sejalan dengan pendekatan sociological jurisprudence yang menekankan bahwa hukum tidak boleh mengabaikan realitas sosial, yakni bahwa biaya hidup layak diukur dari standar minimum regional. Dengan begitu, putusan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan kemanfaatan yang nyata bagi pihak-pihak yang berperkara.