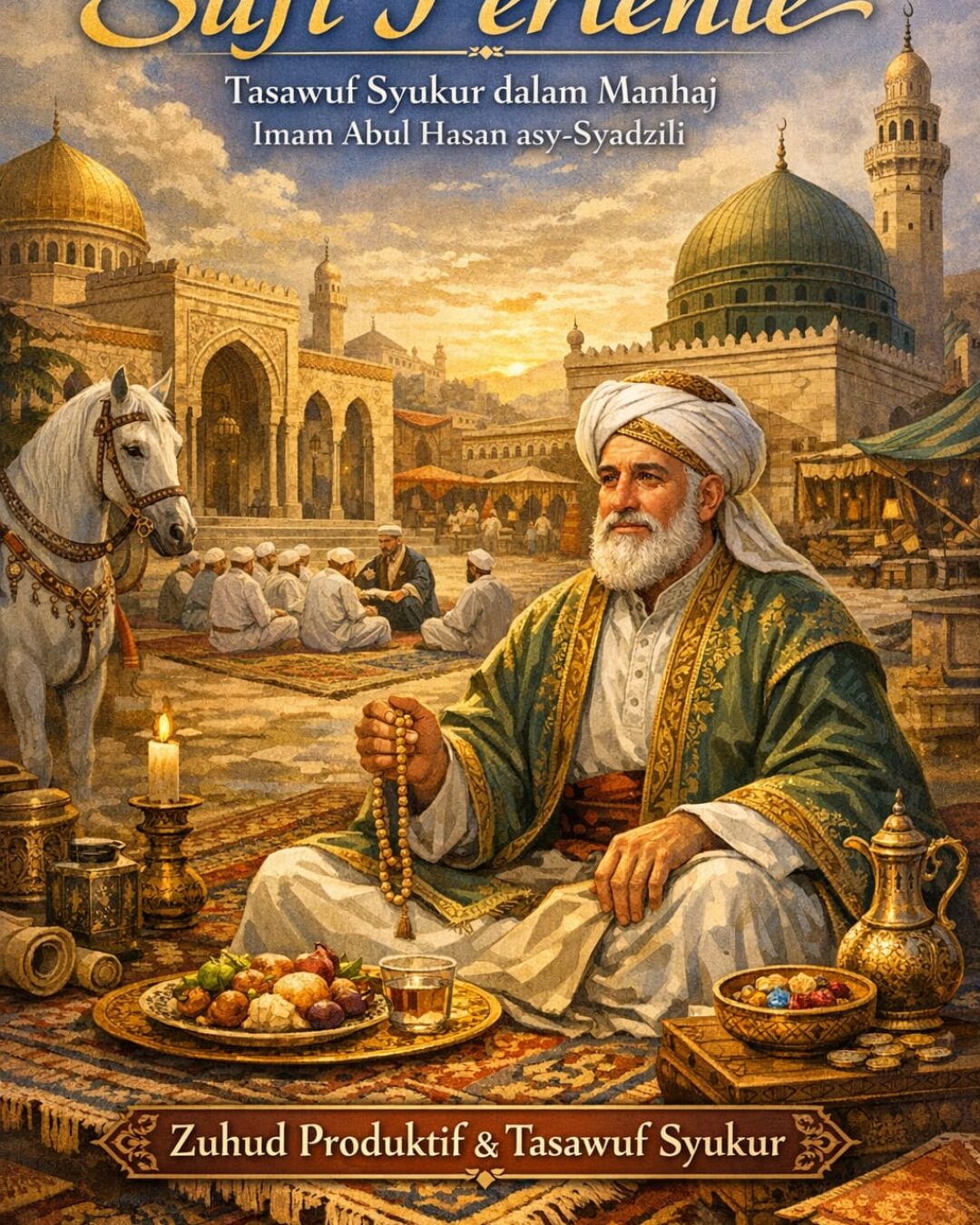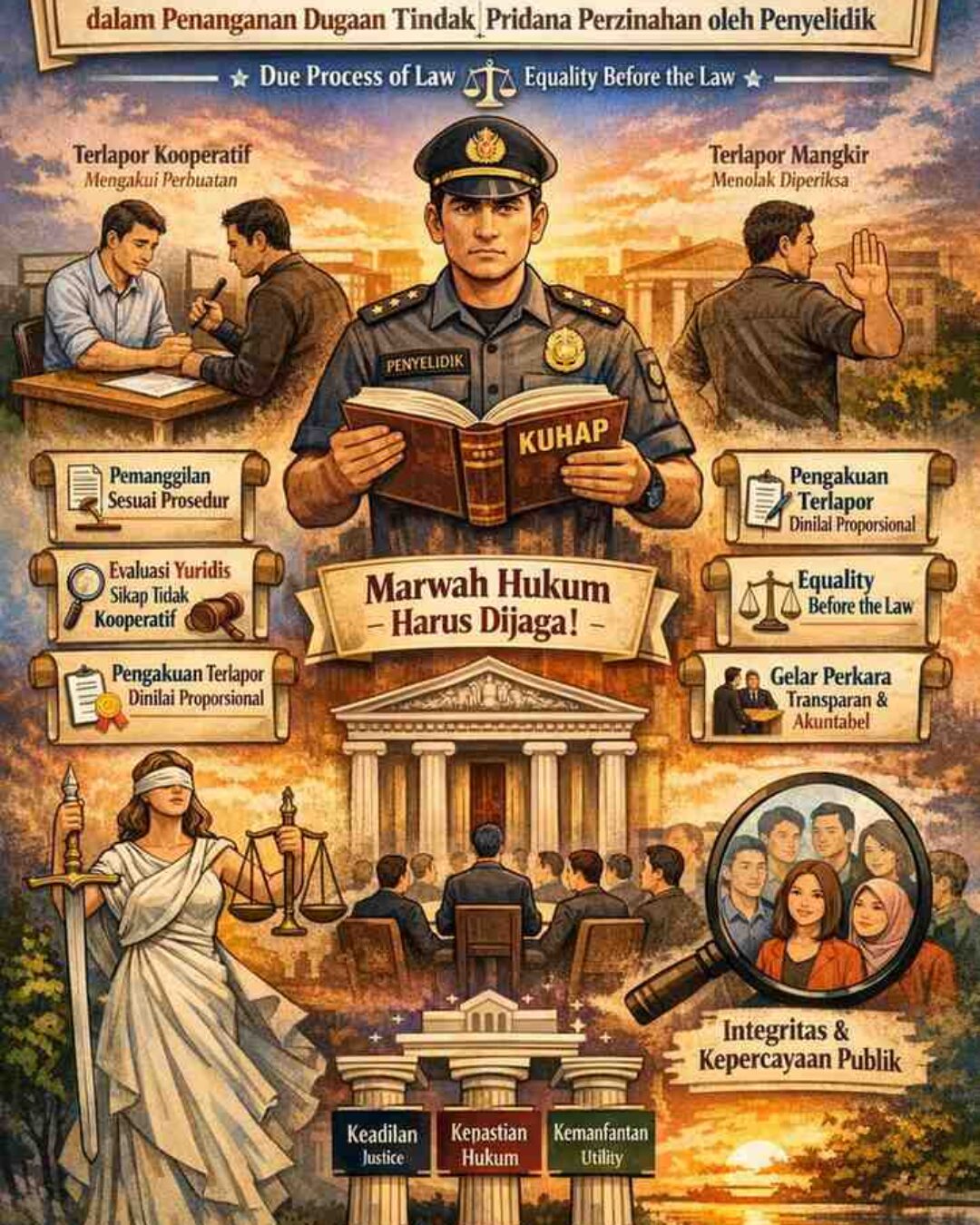Gbr. Ilustrasi
DETIKNUSANTARA.CO.ID – Penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka oleh Polresta Sleman menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum pidana modern, khususnya terkait penerapan asas pembelaan terpaksa (noodweer), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), serta keadaan darurat (overmacht) sebagaimana telah diperbarui dan ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023). Dalam konteks ini, penilaian hukum yang dilakukan penyidik patut dikritisi karena cenderung menempatkan pendekatan formil semata, mengabaikan dimensi psikologis, situasional, dan rasa keadilan substantif yang menjadi roh pembaruan KUHP.
Kronologi sebagai Titik Tolak Analisis Hukum
Hogi Minaya bukanlah pelaku kriminal yang dengan sengaja mencari korban. Ia adalah seorang suami yang istrinya menjadi korban penjambretan, sebuah tindak pidana yang secara nyata merupakan serangan melawan hukum. Reaksi spontan Hogi mengejar pelaku tidak dapat dilepaskan dari kondisi psikologis saat itu: kepanikan, ketakutan, kemarahan, dan naluri protektif untuk melindungi kehormatan serta keselamatan keluarganya.
Dalam hukum pidana modern, konteks adalah segalanya. Tindakan seseorang tidak boleh dinilai secara steril dari situasi yang melingkupinya. Pengejaran yang berujung pada kecelakaan fatal memang merupakan fakta tragis, namun fakta tragis tidak otomatis berarti kesalahan pidana.
Pembelaan Terpaksa dan KUHP Baru
Pasal 34 KUHP Baru menyatakan:
“Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan, atau harta benda.”
Penjambretan adalah serangan seketika, nyata, dan melawan hukum terhadap orang lain, yakni istri Hogi. Dengan demikian, tindakan mengejar pelaku merupakan bentuk pembelaan terhadap serangan yang baru saja terjadi dan berpotensi berlanjut. Tidak ada jeda waktu yang cukup bagi Hogi untuk berpikir rasional dan memilih alternatif hukum yang ideal, seperti melapor ke polisi. Hukum tidak boleh menuntut rasionalitas dingin dalam situasi panas.
Penyidik yang menyatakan bahwa pengejaran tersebut sebagai “pembelaan yang tidak berimbang” telah mengadopsi sudut pandang ex post facto, menilai peristiwa setelah semuanya terjadi, tanpa empati yuridis terhadap situasi ex ante yang dihadapi pelaku.
Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas
Bahkan jika diasumsikan bahwa tindakan Hogi melampaui batas kewajaran, Pasal 43 KUHP Baru memberikan perlindungan hukum:
“Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.”
Kata kunci dalam norma ini adalah “keguncangan jiwa yang hebat”. Menyaksikan pasangan hidup menjadi korban kejahatan jalanan jelas merupakan peristiwa traumatik yang secara psikologis dapat meniadakan kemampuan seseorang untuk bertindak secara terukur. Dalam doktrin hukum pidana, kondisi ini dikenal sebagai psikische overmacht.
Ironisnya, penyidik justru menggunakan keterangan ahli untuk menjustifikasi unsur kesengajaan, namun mengabaikan kemungkinan keguncangan jiwa sebagai faktor peniadaan pidana. Pendekatan ini menunjukkan ketidakberimbangan dalam membaca keterangan ahli, karena hanya menonjolkan aspek teknis pergerakan kendaraan tanpa menilai kondisi mental subjek hukum.
Keadaan Darurat sebagai Alasan Peniadaan Pidana
Pasal 33 KUHP Baru menegaskan:
“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.”
Keadaan darurat tidak selalu harus berupa bencana alam atau ancaman massal. Ancaman serius terhadap keselamatan dan kehormatan keluarga juga merupakan keadaan darurat dalam arti hukum pidana. Dalam hitungan detik, Hogi dihadapkan pada pilihan ekstrem: membiarkan pelaku kabur atau bertindak untuk menghentikan ancaman lanjutan.
Hukum pidana tidak boleh mempidanakan seseorang yang berada dalam dilema moral akut, di mana setiap pilihan mengandung risiko.
Kritik atas Penerapan UU LLAJ
Penggunaan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU LLAJ dalam perkara ini juga problematik. Kedua pasal tersebut dirancang untuk perilaku berkendara yang secara normal dan otonom berbahaya, bukan untuk situasi luar biasa yang dipicu tindak pidana lain.
Mengabaikan konteks awal berupa penjambretan berarti memisahkan sebab dan akibat secara artifisial. Padahal, dalam asas hukum pidana dikenal prinsip causa proxima, sebab terdekat dari peristiwa hukum. Dalam kasus ini, sebab utama kematian bukanlah niat Hogi, melainkan rangkaian peristiwa kriminal yang dimulai oleh penjambret.
Restorative Justice sebagai Pengakuan Implisit
Kesediaan aparat penegak hukum untuk mendorong penyelesaian melalui restorative justice sejatinya merupakan pengakuan implisit bahwa perkara ini tidak murni layak diperlakukan sebagai kejahatan konvensional. Fakta bahwa tidak dilakukan penahanan karena Hogi kooperatif, tidak berisiko melarikan diri, dan memiliki iktikad baik, semakin menegaskan bahwa unsur kesalahan subjektifnya lemah.
Penutup: Hukum untuk Manusia, Bukan Sekadar Teks
KUHP Baru lahir untuk memanusiakan hukum pidana Indonesia. Menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka tanpa mengakui pembelaan terpaksa, keguncangan jiwa, dan keadaan darurat adalah kemunduran dari semangat tersebut.
Hukum tidak boleh menjadi mesin dingin yang menghukum orang baik yang berada di tempat dan waktu yang salah. Dalam perkara ini, yang patut dimintai pertanggungjawaban moral dan hukum pertama-tama adalah pelaku kejahatan jalanan, bukan korban sekunder yang bereaksi dalam kepanikan.
Jika hukum kehilangan empati, maka keadilan hanya akan menjadi ilusi prosedural.
- [A. MUKHOFFI, S.H., M.H.]
- Ketua LPBH PCNU Kraksaan
- Ketua Bid. Hukum, HAM, & Hub. Lembaga Negara MPC Pemuda Pancasila Kab. Probolinggo
- Ketua Bid. Hukum Libas88 Nusantara