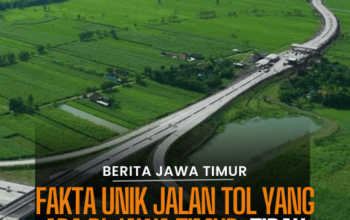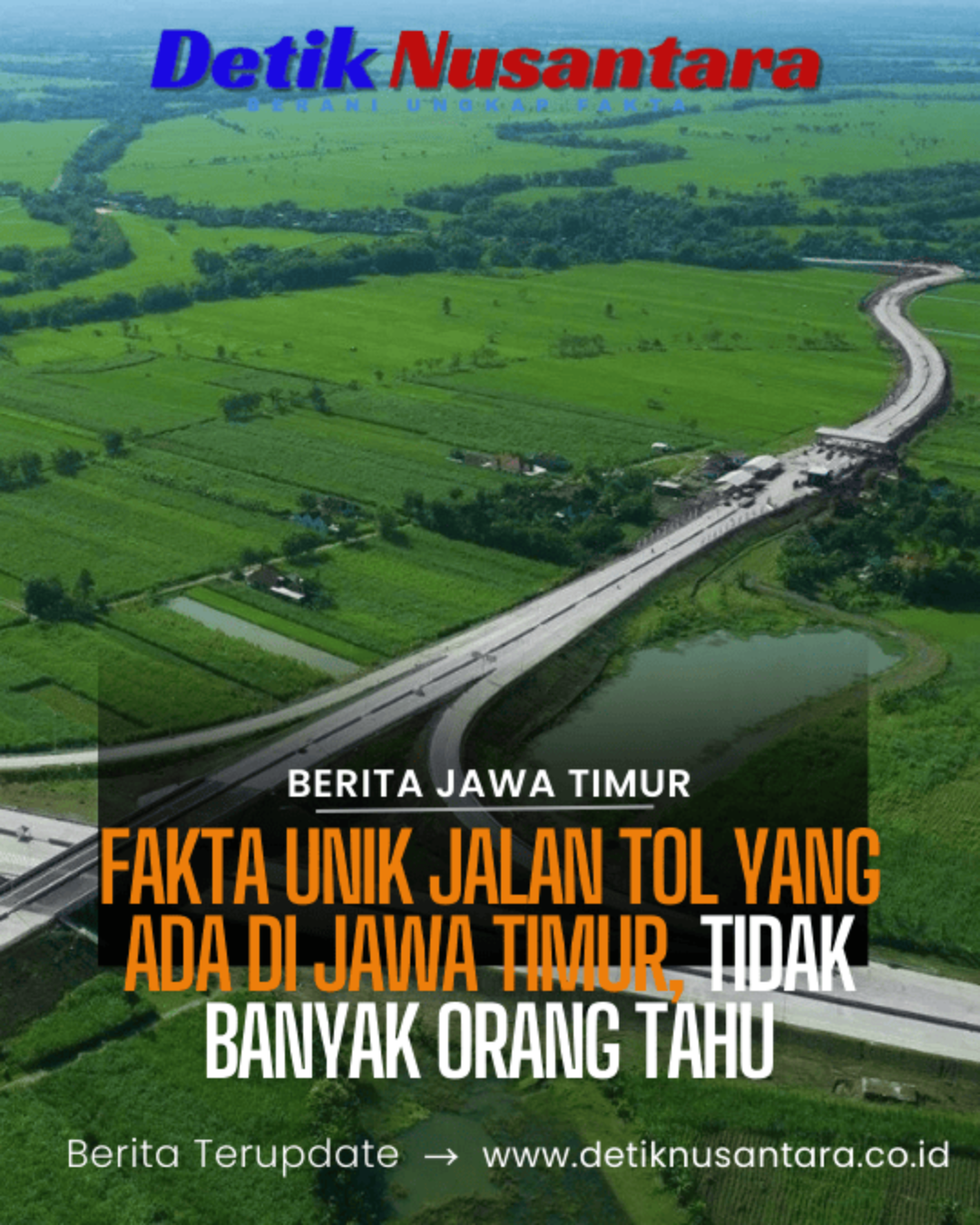DetikNusantara.co.id – Permasalahan mengenai dapat atau tidaknya pelaku pengalihan objek jaminan fidusia dijerat dengan Pasal 372 KUHP sesungguhnya menyentuh aspek mendasar dalam teori pertanggungjawaban pidana dan asas penerapan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum.
Secara dogmatis, Pasal 372 KUHP mengandung esensi delik verduistering (penggelapan), yang menitikberatkan pada adanya penguasaan atas suatu barang oleh pelaku, kemudian menimbulkan animus rem sibi habendi atau kehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam pasal ini mensyaratkan bahwa penguasaan yang lahir dari suatu hubungan hukum privat berubah menjadi penguasaan yang menyalahi norma hukum pidana, karena adanya intensi untuk meniadakan hak pihak lain.
Namun, dalam konteks jaminan fidusia, penguasaan objek jaminan oleh debitur pada dasarnya bukanlah penguasaan yang lahir dari hubungan tanpa dasar hukum, melainkan penguasaan yang berakar pada perjanjian yang sah dan diakui oleh hukum perdata maupun hukum benda. Objek jaminan fidusia secara prinsip masih berada dalam kepemilikan yuridis kreditur penerima fidusia, tetapi secara faktual dikuasai debitur untuk mendukung kegiatan ekonominya. Dengan demikian, penguasaan tersebut tidak memenuhi elemen dasar yang lazim dipersyaratkan dalam konstruksi delik penggelapan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP.
Lebih lanjut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara eksplisit mengatur larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Norma pidana ini bersifat lex specialis karena dibuat untuk secara khusus mengatur penyimpangan terhadap rezim hukum fidusia, yang dalam kodifikasi KUH Perdata maupun KUHP tidak diatur secara rinci. Doktrin lex specialis derogat legi generali memberikan landasan bahwa ketika suatu perbuatan telah dirumuskan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan khusus, maka keberlakuan ketentuan umum harus dikesampingkan.
Dengan demikian, secara teoritik maupun normatif, penggunaan Pasal 372 KUHP terhadap pengalihan objek fidusia tidak hanya mengaburkan batas antara penguasaan sah dan penguasaan tanpa hak, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Instrumen yang tepat adalah Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, karena norma ini memang dibentuk dengan mempertimbangkan karakteristik hubungan hukum fidusia yang unik—yaitu dualisme antara kepemilikan yuridis kreditur dengan penguasaan faktual debitur.
Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak semestinya dijerat dengan Pasal 372 KUHP, melainkan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Argumentasi ini bukan semata bersandar pada asas lex specialis, tetapi juga pada prinsip legal certainty (kepastian hukum) dan fair labeling, yakni keharusan bahwa setiap perbuatan pidana dikualifikasikan sesuai dengan karakter normatif yang melekat padanya.