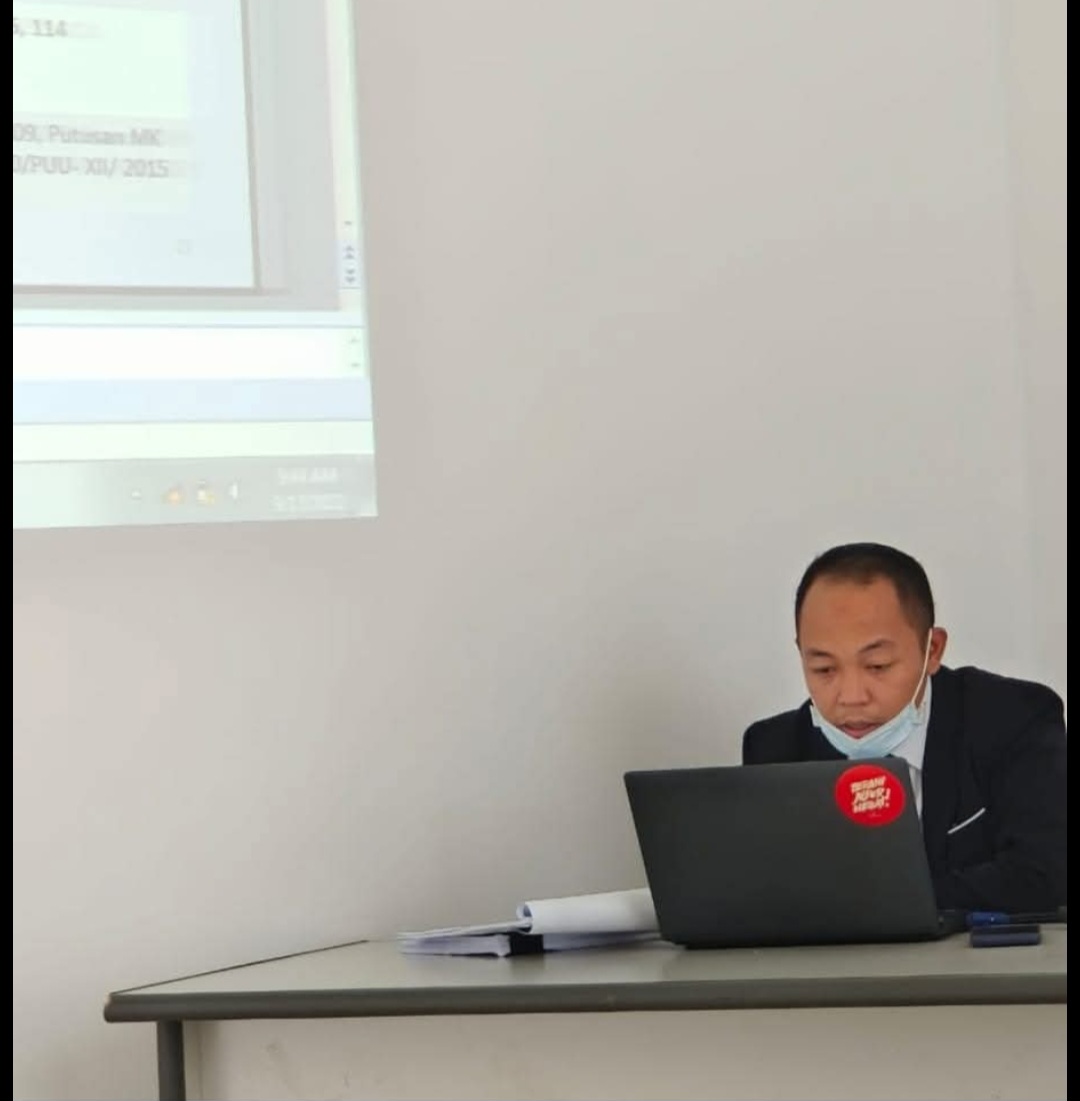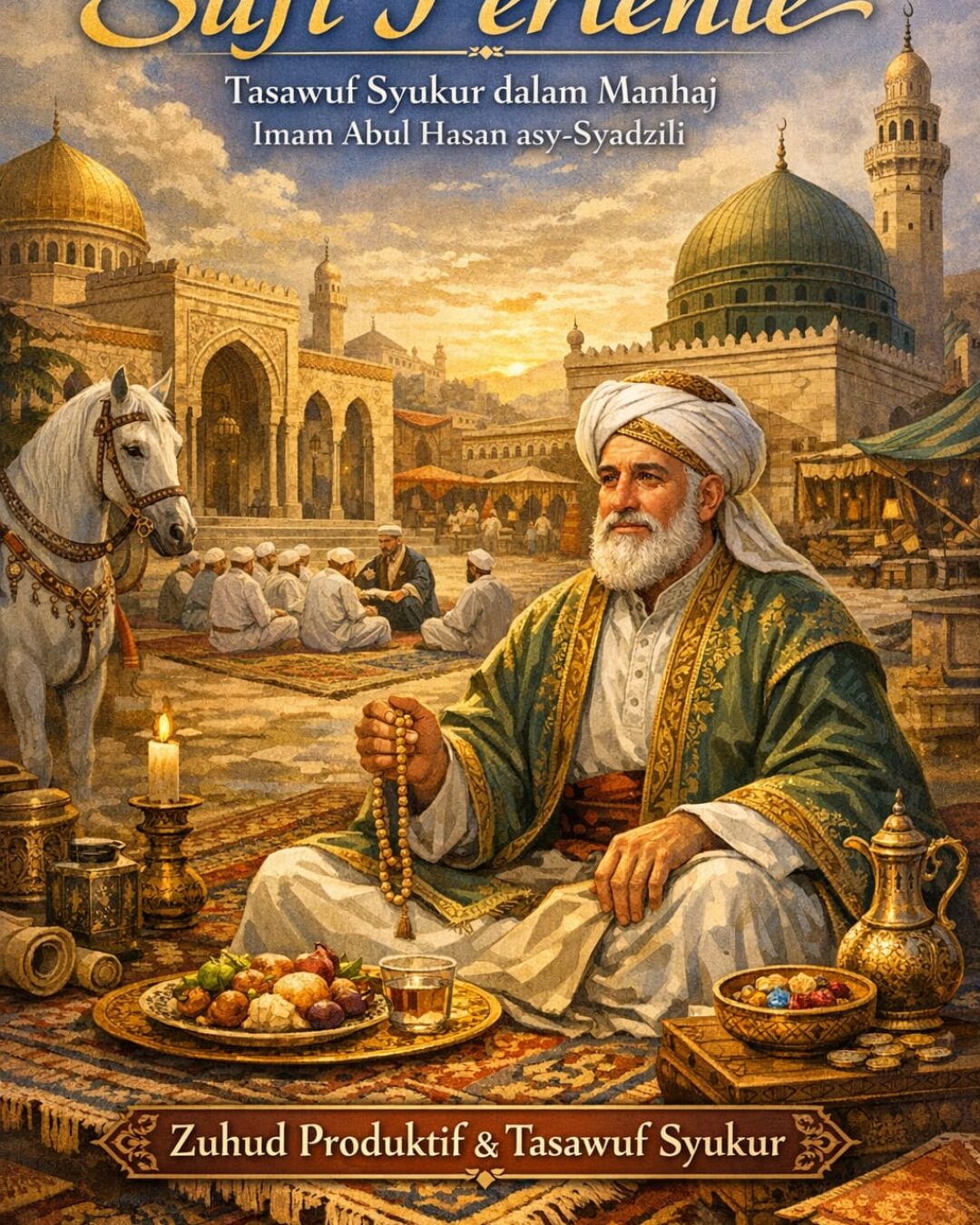Persoalan penerapan pidana minimum dalam tindak pidana narkotika, khususnya pada perkara penyalahgunaan sabu dengan barang bukti kurang dari 1 (satu) gram, merupakan problem fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Norma pidana minimum yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika pada hakikatnya dimaksudkan sebagai deterrent effect untuk menekan angka kejahatan narkotika. Akan tetapi, secara empiris norma tersebut kerap menimbulkan disparitas penjatuhan pidana yang justru bertentangan dengan asas keseragaman penerapan hukum (equality before the law).
Secara teoritik, penerapan pidana minimum dalam jumlah barang bukti yang sangat kecil menimbulkan ketidakselarasan dengan prinsip proporsionalitas. Dalam doktrin hukum pidana modern, asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara derajat kesalahan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan beratnya pidana yang dijatuhkan. Apabila pengadilan tetap kaku dalam menerapkan pidana minimum, maka seorang terdakwa dengan bobot netto barang bukti kurang dari 1 gram dapat dijatuhi pidana yang sama beratnya dengan pelaku peredaran gelap dengan puluhan gram sabu. Hal ini tidak hanya menciderai rasa keadilan, melainkan juga menyalahi asas culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan yang sepadan).
Lebih lanjut, secara konstitusional pengadilan memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menyeimbangkan norma hukum yang rigid dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa hakim bukan semata corong undang-undang (la bouche de la loi), tetapi juga merupakan pengemban nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, pengadilan memiliki legitimasi normatif untuk melakukan penyimpangan terhadap pidana minimum, sepanjang hal itu dilakukan demi pemenuhan asas keadilan substantif dan keseragaman penerapan hukum.
Secara doktrinal, langkah ini berakar pada teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum bukan sebagai teks yang kaku, melainkan instrumen yang hidup dan bergerak sesuai kebutuhan keadilan. Dalam kerangka tersebut, penyimpangan pidana minimum pada kasus sabu di bawah 1 gram bukanlah bentuk contra legem (bertentangan dengan undang-undang), melainkan contra injustice (penolakan terhadap ketidakadilan). Hakim yang progresif justru sedang menegakkan hukum dalam arti substantif dengan cara menghindarkan disparitas pidana antar putusan.
Di samping itu, penting pula dicatat bahwa penyalah guna narkotika dengan barang bukti sangat kecil lebih dekat pada konstruksi “korban” daripada “pelaku peredaran”. Oleh karena itu, pemidanaan dengan instrumen pidana minimum berpotensi melanggar asas ultimum remedium, sebab seharusnya pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan dibandingkan pemenjaraan jangka panjang.
Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pengadilan harus diperkenankan, bahkan berkewajiban secara moral dan konstitusional, untuk menyimpangi pidana minimum pada kasus sabu dengan barang bukti di bawah 1 gram. Langkah ini bukan sekadar bentuk diskresi yudisial, melainkan instrumen menjaga keseragaman penerapan hukum, menjamin asas proporsionalitas, serta menegakkan keadilan substantif dalam hukum pidana nasional.