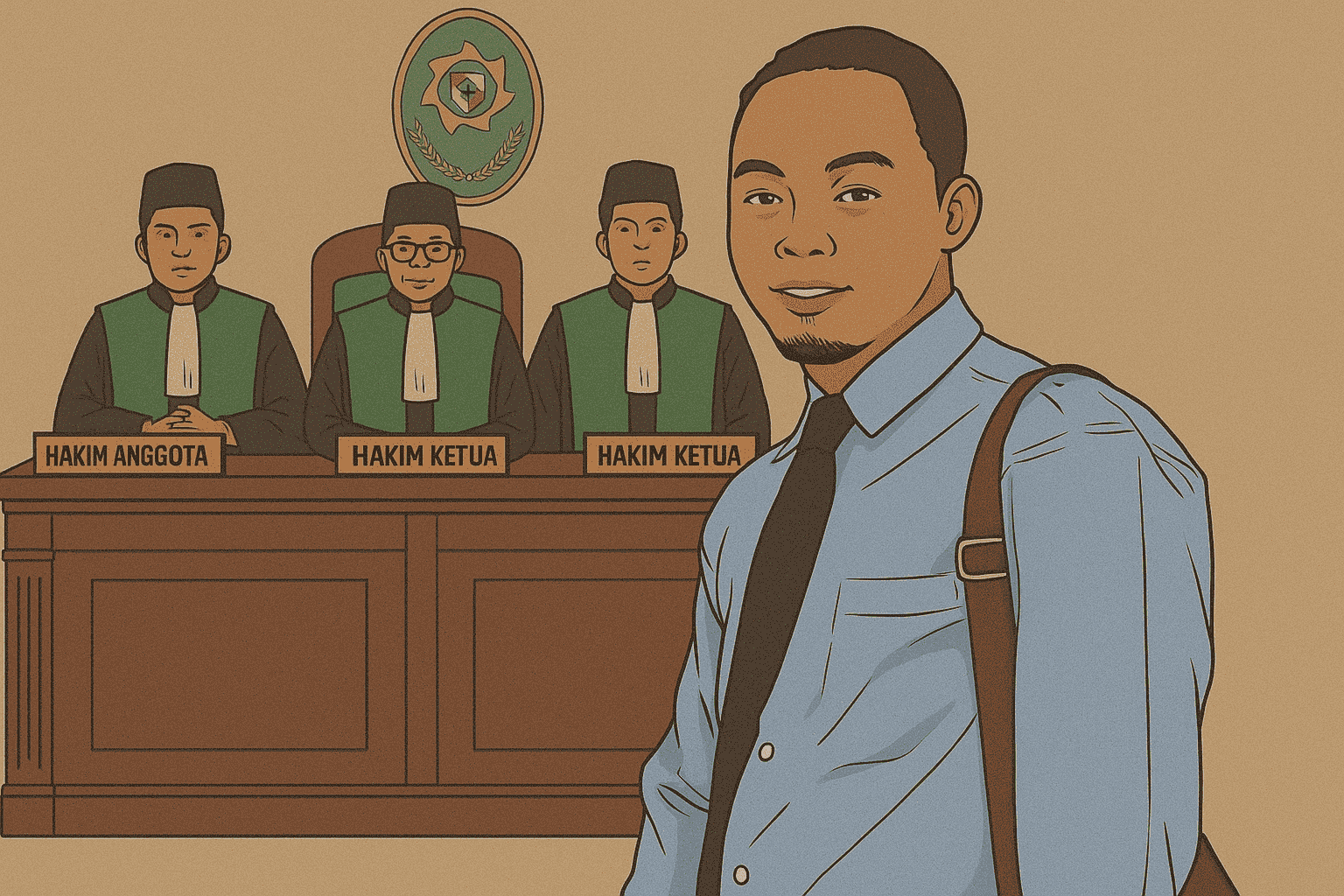Detiknusantara.co.id – Kehadiran pribadi para prinsipal dalam perkara perceraian untuk didamaikan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) merupakan norma klasik yang dibangun dalam kerangka hukum acara konvensional. Norma tersebut berlandaskan pada filosofi bahwa perceraian adalah langkah terakhir (ultimum remedium) setelah semua upaya damai dilakukan secara langsung oleh hakim sebagai representasi negara.
Secara normatif, Pasal 82 ayat (1) menyatakan:
“Pada setiap sidang pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.”
Kemudian, ayat (2) menegaskan:
“Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”.
Lalu, ayat (3):
(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
Ketiga ketentuan tersebut secara implisit mengandung kewajiban kehadiran prinsipal secara langsung, sebab esensi dari “mendamaikan” oleh hakim sulit dicapai tanpa pertemuan tatap muka. Namun, konstruksi norma ini lahir dalam masa di mana mekanisme mediasi belum terinstitusionalisasi dalam hukum acara peradilan.
Kelahiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum acara perdata di Indonesia. Perma ini menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib (mandatory process) sebelum pemeriksaan pokok perkara. Dalam kerangka ini, fungsi hakim sebagai mediator langsung bergeser menjadi fungsi pengawasan terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh mediator bersertifikat.
Secara substantif, Perma ini membawa tiga perubahan mendasar terhadap filosofi perdamaian dalam peradilan agama:
1. Delegasi fungsional kewenangan damai dari hakim pemeriksa kepada mediator profesional.
2. Perluasan metode mediasi, termasuk mediasi elektronik (online mediation) yang mengakomodasi perkembangan teknologi dan kondisi para pihak.
3. Legitimasi hasil mediasi yang diatur secara formal, baik dalam bentuk kesepakatan damai (akta perdamaian/akta van dading) maupun berita acara tidak tercapai kesepakatan.
Dengan demikian, secara yuridis dan fungsional, upaya damai yang diwajibkan oleh Pasal 82 UU Peradilan Agama telah termaterialisasi dalam institusi mediasi sebagaimana diatur dalam Perma 1/2016.
Dalam perspektif teori hierarki norma hukum (Stufenbau des Rechts) ala Hans Kelsen, Perma memang berada di bawah Undang-Undang. Namun, dalam praktik peradilan modern, keberlakuan norma hukum tidak hanya ditentukan oleh hierarki, melainkan juga oleh fungsi dan efektivitas normatifnya. Pasal 82 UU Peradilan Agama kini menghadapi apa yang disebut sebagai functional derogation, yaitu penggeseran makna dan relevansi norma akibat perkembangan sistem hukum yang lebih adaptif.
Kewajiban kehadiran prinsipal untuk didamaikan langsung oleh hakim telah menjadi redundan (duplikasi normatif) karena esensi perdamaian telah diwadahi melalui mediasi yang lebih sistematis. Lebih jauh, keharusan tersebut kerap berpotensi melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, terutama ketika para pihak berdomisili jauh atau menghadapi hambatan sosial-psikologis yang membuat pertemuan langsung tidak produktif.
Dalam konteks sosiologis, perkembangan masyarakat modern dengan mobilitas tinggi, kompleksitas pekerjaan, serta dinamika relasi keluarga menuntut fleksibilitas dalam hukum acara. Kehadiran pribadi para pihak di pengadilan tidak lagi menjadi satu-satunya indikator itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa. Justru, proses mediasi memberikan ruang yang lebih aman, adaptif, dan netral untuk membangun komunikasi yang konstruktif tanpa tekanan psikologis dari situasi ruang sidang.
Dari perspektif teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo), hukum harus melayani kebutuhan manusia dan bergerak mengikuti perubahan sosial. Oleh karena itu, tafsir terhadap Pasal 82 UU Peradilan Agama tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus ditafsirkan secara teleologis, yakni menekankan pada tujuan hukum, bukan pada formalisme prosedural.
Dengan demikian, kewajiban kehadiran pribadi para prinsipal untuk didamaikan langsung oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Peradilan Agama telah kehilangan relevansi yuridis dan sosiologisnya setelah lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Upaya damai oleh hakim kini seharusnya dimaknai sebagai pengawasan terhadap proses mediasi yang merupakan tahapan formal dan substantif dari perdamaian dalam sistem peradilan modern.
Reorientasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bentuk penyesuaian hukum terhadap realitas baru, di mana substansi keadilan dan efektivitas penyelesaian sengketa lebih diutamakan daripada rigiditas prosedural. Maka, tafsir progresif terhadap Pasal 82 UU Peradilan Agama merupakan keniscayaan agar peradilan agama tetap relevan dalam sistem hukum nasional yang terus berkembang.